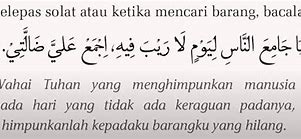Perjalanan Menjadi Dewa
Jatuh dari keningratan, Zen Luo menjadi budak yang rendahan yang digunakan sebagai karung tinju untuk para mantan sepupunya. Secara tidak sengaja, dia menemukan cara untuk mengasah dirinya menjadi senjata dan sebuah legenda dimulai karena itu. Dengan keyakinan yang kuat untuk tidak pernah menyerah, dia berusaha untuk membalas dendam dan mengejar impian yang besar. Pendekar dari berbagai klan bersaing untuk kekuasaan dan dunia menjadi kacau. Mengandalkan tubuh yang sebanding dengan senjata ampuh, Zen mengalahkan banyak musuh dalam perjalanannya menuju keabadian. Akankah dia berhasil pada akhirnya?
Cinderella Pulang Pagi
Apa yang kamu lakukan jika tunanganmu meninggalkanmu dan memutuskan untuk menikah dengan wanita lain saat pernikahan kalian sudah dekat? Menangis semalaman karena patah hati atau bermain cantik untuk membalas dendam pada mereka yang melukaimu? Ya, Elaina bukan Cinderella, namun ia kehilangan sebelah
Novel Paling Banyak Dicari
Rinai Hujan di Pagi Hari
Kania Lim dan Melani Lim adalah sepasang kakak adik yang jatuh cinta pada satu lelaki, Sammy. Bahagia Kania rasakan ketika Sammy memilihnya menjadi kekasih. Namun, Kania terpaksa merelakan Sammy menikahi Melani akibat kecelakaan yang membuat sang kakak harus kehilangan tangan kirinya. Kania menerima
Perbedaan status sosial membuat hubungan antara Jean dan Lisa terpaksa kandas dan membuat kehidupan Jean hancur. Sedangkan Lisa memilih untuk menjalin hubungan dengan lelaki baru sekalipun dijalani dengan setengah hati. Namun takdir mempertemukan mereka kembali. Hati yang dulu mencinta kini berubah
MASIH ADAKAH MAKNA 39
Wanita yang memungut uang Rohana, jatuh terjengkang. Rohana marah bukan alang kepalang.
“Lisa! Apa yang kamu lakukan?”
“Bodoh kamu Rohana! Uangmu berserakan dan si miskin itu memungutinya. Apa karena uangmu terlalu banyak sehingga membiarkan dia mencurinya?”
“Saya tidak mencuri. Saya hanya membantu,” kata wanita itu sambil bangkit.
Rohana segera tahu, dialah wanita yang dicarinya.
Ia menerima uang yang tadinya diambilkan wanita itu, dan membantunya berdiri.
“Apa yang membuatmu berubah Rohana? Kamu sudah tidak sekaya dulu, dan pura-pura menjadi wanita baik?”
Rohana menggandeng wanita itu dan mengajaknya masuk ke arah ruangan yang tidak berkelas.
Lisa mencibir sambil membalikkan badannya, tapi ia tak sadar, seorang perawat sedang mendorong seperangkat peralatan yang sebagian besar terbuat dari kaca. Lisa jatuh tertelungkup, dan sebatang pecahan bejana kaca menancap di sebelah matanya.
Jeritannya terdengar bagaikan lolongan yang membelah suasana tenang di pagi itu. Rohana menoleh dan terbelalak. Ia melihat beberapa perawat mengangkat Lisa yang wajahnya bercucuran darah.
“Lisa! Apa yang terjadi?”
Walau kesal, tapi rasa iba memenuhi hati Rohana. Wajah Lisa berlumuran darah, dan perawat langsung mengangkatnya ke atas brankar, melarikannya ke UGD.
“Ya Tuhan, sebiji mata Lisa tak sebanding dengan seluruh harta yang dimilikinya. Mengapa dia bisa sesombong itu? Semoga dia baik-baik saja,” gumamnya sedih.
“Kenapa Bu?” tanya wanita yang tadi digandeng Rohana.
“Entah bagaimana, aku juga tak melihatnya, sepertinya dia menabrak dorongan itu,” kata Rohana yang melihat beberapa petugas membersihkan beberapa perangkat alat kesehatan yang berantakan dan pecah.
“Sebenarnya saya mau membeli obat lagi,” kata wanita itu.
“Oh ya? Bagaimana keadaan anakmu?”
“Sudah tidak seperti kemarin. Tapi masih belum mau makan. Katanya perutnya sakit.”
“Berapa harga obatnya?”
“Entahlah, saya baru mau ke apotek.”
“Oh, baiklah, ayo ke apotek. Uangnya masih ada?”
“Ada, semoga cukup. Terima kasih telah membantu menyambung nyawa anakku,” kata wanita itu haru.
“Berterima kasihlah kepada Allah, aku tidak melakukan apa-apa. Semua karena Allah.”
Wanita itu mengangguk. Kata-kata ‘karena Allah’ itu menusuk nuraninya. Apakah selama ini dia mengenal Allah? Matanya berkaca-kaca. Karena ia tak mengenalNya, maka hidupnya terasa sengsara?
“Katakan kepadaku, bagaimana mengenal Allah.”
“Ia begitu dekat denganmu, tapi kamu tidak mengenalnya?” kata Rohana yang entah darimana datangnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Barangkali karena dia juga lama sekali melupakan Junjungannya, lalu ketika kemudian mengenalnya, maka ia bisa mengatakannya kepada orang lain. Bukankah ia menemukan ketenangan saat bersujud, saat memohon ampun dan petunjukNya, saat menangis menyesali semua perbuatannya?
“Pergilah ke apotek, setelah itu marilah kita menemuiNya dalam sujud dan penyesalan atas semua dosa kita.”
Wanita itu beranjak ke apotek, dan Rohana pergi keluar. Ia membeli beberapa potong pakaian orang dewasa, beberapa jilbab, dan beberapa pakaian anak kecil seumur tiga tahunan, juga handuk, sabun dan alat pembersih yang lain. lalu ia kembali masuk ke rumah sakit. Ketika melewati ruang UGD, ia mendengar suara jeritan. Hatinya sangat miris. Lisa sedang ditangani, dan menjerit-jerit kesakitan.
Rohana merasa tak bisa berbuat apa-apa. Ia melihat pembantu Lisa sudah duduk di ruang tunggu dengan gelisah.
Ia menanyakan keadaan LIsa, tapi mana mungkin pembantu itu bisa menjawabnya? Ia hanya menunggu, dan pastinya sudah mengabari keluarganya.
“Semoga Lisa baik-baik saja,” bisiknya tulus.
Rohana menuju ke arah apotek. Wanita yang belum diketahui siapa namanya itu duduk di sana. Rohana mendekat dan memberikan bungkusan yang dibawanya.
“Kamu mandilah, dan ganti pakaian kamu. Ini ada juga pakaian untuk anakmu.”
Tangan wanita itu gemetar menerimanya.
“Kamu benar-benar seperti malaikat,” bisiknya pelan sambil matanya berkaca-kaca.
“Ssssh, sudahlah. Oh ya, berapa harga obatnya?”
“Hanya tujuh puluh ribu. Katanya obatnya berupa infus. Perawat di ruangan Bejo mengatakan bahwa akan ada tagihan ruang rawat juga. Setelah ini aku akan pergi untuk mencari uang. Bejo sedang tidur.”
Jadi anak kecil itu namanya Bejo?
“Kalau ibu namanya siapa? Saya nenek Rohana.”
“Oh, iya. Saya sudah menerima banyak kebaikan dari Nenek, tapi belum memperkenalkan diri. Saya Kartinah. Suami saya sudah meninggal ketika Bejo masih bayi.”
“Kamu tahu? Meminta-minta bukan perbuatan yang bagus.”
“Lalu saya harus bagaimana? Saya orang miskin, bisanya hanya meminta. Tempat tinggalpun tak mampu menyewanya."
“Lakukan sesuatu. Misalnya berjualan.”
“Jualan apa? Harus ada modal untuk itu.”
“Setelah anakmu sembuh, carilah tempat untuk beristirahat, menyewa yang murah misalnya, lalu berjualanlah. Kamu bisa membuat gorengan, atau memasak masakan yang bisa dijual, atau apa, pikirkanlah mana yang bisa kamu lakukan.”
Kartinah menggenggam tangan Rohana sangat erat.
“Nanti aku bantu kamu mencari rumah sewa, aku yang membayar untuk setengah tahun ke depan, lalu aku berikan kamu modal beberapa, lalu kamu sisihkan uang untuk sewa berikutnya, sambil terus berjualan. Niatkanlah usaha itu untuk sesuatu yang berguna. Semoga kamu berhasil.”
“Nenek,” haru hati Kartinah tak tertahankan.
Ketika petugas apotek memanggil nama Bejo, ia berdiri sambil mengusap lagi air matanya.
Kartinah sudah kembali ke ruang anaknya, tapi Rohana masih mampir lagi ke depan ruang UGD. Pembantu Lisa kelihatan masih saja gelisah. Keluarganya sudah ada yang datang, katanya sedang menemui dokter. Tapi pembantu itu sedih, pembicaraan yang didengar, sebelah mata Lisa tak bisa diselamatkan. Rohana terpana mendengarnya. Berarti Lisa akan menjadi buta? Ia kesal terhadap temannya yang satu ini, tapi mendengar sebelah matanya kemungkinan menjadi buta, hatinya sedih bukan alang kepalang. Apa yang dipikirkannya benar bukan? Sebelah mata tak sebanding dengan harta yang dimilikinya. Kalau harus memilih, mana yang akan dipilih, memiliki mata yang utuh, atau harta yang berlimpah ruah?
Tak ada seorangpun memilih harta, karena perlengkapan tubuh yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Murah, bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan semua harta yang ada di dunia ini. Allah Maha Besar.
Rohana pulang dengan perasaan murung.
Ketika ia hampir sampai di pintu keluar, sebuah mobil berhenti. Kaca depan mobil itu terbuka, dan Rohana melihat Boy ada di dalamnya.
Boy memarkirkan mobilnya, lalu ia mendekati sang nenek.
“Nenek dari membezoek kakek?”
Rohana menggelengkan kepalanya. Ia tahu sang nenek bukannya benci kepada kakeknya, tapi selalu merasa sungkan setiap kali berdekatan dengannya. Jadi kalau ingin membezoek kakeknya, pastilah kalau sedang bersama anak-anak atau cucunya.
“Membezoek seseorang.”
"Nenek jangan pulang sendiri, nanti Boy antarkan. Tapi sekarang Boy mau mengirimkan makanan pesanan kakek.”
Tak ada alasan untuk menolaknya, kecuali mengangguk.
“Nenek harus punya ponsel, nanti Boy belikan.” kata Boy sambil berjalan ke arah dalam, dimana kakeknya dirawat.
“Supaya gampang kalau kita mau menghubungi Nenek.”
“Nenek kan sudah bilang kalau ada keperluan, mengapa harus dihubungi? Apa kalian takut nenek akan pergi dan tak akan kembali?”
“Bukan begitu Nek. Terkadang ada berita yang nenek harus mengetahuinya. Misalnya ada yang mencari Nenek.”
“Nenek kan tidak punya teman. Kalaupun ada, hanya teman yang pasti akan merendahkan nenek dengan keadaan ini.”
“Tapi Nenek bukan orang rendah. Nenek adalah setinggi-tingginya wanita yang Boy junjung dan cintai.”
“Jangan, nanti nenek jatuh.”
“Sudah, diamlah. Jangan bicara yang aneh-aneh. Biasa saja,” katanya dengan mulut cemberut.
Tapi ketika ia memasuki ruangan rawat pak Drajat, cemberut itu hilang karena pak Drajat menyapanya dengan ramah.
“Rohana? Kamu baik-baik saja?”
“Ya. Aku baik. Semoga keadaanmu juga lebih baik.”
“Tentu saja, aku sudah mau minta pulang.”
“Kakek, jangan tergesa pulang. Nanti kalau dokter sudah bilang oke, baru Kakek boleh pulang.”
“Dokter itu selalu mengatakan tunggu … tunggu … memangnya aku kenapa? Aku merasa baik. Sebal sekali tanganku diikat dengan segala macam infus itu.”
“Ya sudah, nanti Boy tanyakan pada dokter, apa Kakek sudah sehat atau belum.”
“Tanya bukan kepada dokter, tapi kepada kakek ini, kan kakek yang merasakannya.”
Rohana menahan senyumnya. Pak Drajat memang keras kepala. Ia sukar diatur, tapi sangat tegas. Itu pula sebabnya ia sangat marah ketika melihat dirinya sedang mendekati pak Ratman ketika terlibat hutang.
“Ini masakan ibu Minar. Baru saja Boy ambil di rumahnya.”
“Iya, aku memesan sup ayam dari dia. Aku ingin makan sekarang. Masih hangatkah?”
“Masih agak panas. Boy ambilkan dulu di mangkuk.”
Rohana undur ke belakang, duduk di sofa, agak jauh dari tempat pak Drajat berbaring. Sungkan menunggui bekas suaminya makan. Takutnya Boy meminta Rohana menyuapinya. Aneh kan?
“Minar selalu memasak enak. Tapi ibumu juga masakannya luar biasa enak. Hanya saja aku terkesan ketika kemarin dia membawakan sup ayam, jadi aku ingin memakannya lagi.”
“Iya, ibu Minar tidak lupa, karenanya pagi tadi Boy ditelponnya.”
“Bagaimana rencana pernikahan kalian?”
“Kakek harus sembuh dulu, baru bicara tentang pernikahan Boy.”
“Karena itulah aku ingin segera pulang.”
“Tidak tergesa-gesa, Kakek. Semuanya sudah disiapkan, tinggal menunggu Kakek sembuh.”
“Benar? Kamu tidak kekurangan uang?”
“Tentu saja tidak. Kakek tidak usah memikirkannya.”
“Apa nenekmu itu tinggal di rumahmu?” kali ini pak Drajat bicara pelan.
“Iya. Kakek keberatan?”
Pak Drajat menggoyang-goyangkan tangannya, karena mulutnya sedang mengunyah gurihnya daging ayam yang baru saja disuapkan cucunya.
"Ada pavilyun yang tidak terpakai. Buat lebih pantas agar dia bisa tinggal lebih nyaman dan bisa melakukan apa yang dia inginkan,” katanya, masih dengan sepelan mungkin.
“Baik, Kakek. Terima kasih atas kebaikan Kakek.”
“Mengapa harus berterima kasih?” kali ini suaranya lebih keras.
“Sudah, aku sudah kenyang. Buat nanti lagi,” katanya sambil meraih tissue untuk mengelap mulutnya. Boy mengambilkan minum dan pak Drajat menyedotnya dengan rasa puas.
“Sekarang kalian pulanglah, sebentar lagi Ratman akan datang dan menemani kakek ngobrol."
“Bukankah kakek belum boleh bicara banyak?”
“Apa maksudmu? Bagaimana kalau kemudian aku lupa cara orang berbicara?”
Boy tergelak. Sang kakek selalu bicara sembarangan, dan terkadang lucu. Tapi ia senang, sang kakek sudah tidak sepucat kemarin.
Boy mengantarkan nenek Rohana. Ia mampir ke toko ponsel, lalu memaksa sang nenek untuk menerima ponsel itu, membuat Rohana bersungut-sungut sampai kemudian memasuki rumah Tomy.
Monik yang melayani makan sang ibu mertua, hanya tersenyum ketika mendengarnya mengomel tentang ponsel itu.
“Bu, itu kan penting, untuk berkomunikasi.”
“Seperti orang penting saja. Aku biasa saja kan?”
“Bukan begitu, terkadang ketika ibu pergi, kita ingin bicara tentang sesuatu.”
“Bukankah bisa bicara di rumah?”
“Atau ketika Monik ingin nitip makanan tertentu, agar ibu membelikannya, ketika ibu sedang dijalan, dan Monik lupa bilang sebelum berangkat. Ya kan?”
“Hanya masalah makanan …”
“Sudahlah Bu, diterima saja. Pada suatu waktu, pasti ibu memerlukannya.”
Rohana hanya melanjutkan makan. Makanan dengan menu yang dulu disukainya. Rendang daging dari masakan Padang, yang pedasnya selangit. Dulu dia selalu memakannya dengan lahap, ketika sedang mendapat rejeki dan dia berhasil membelinya. Tapi sekarang biasa saja. Ia mengunyahnya seperti ia mengunyah makanan sederhana. Tahu, tempe, bahkan ikan asin.
“Nambah Bu,” tawar Monik.
“Sudah kenyang. Orang tua itu perutnya sudah menyempit, tidak akan muat menerima makanan banyak, nanti bisa meletus perutku.”
“Monik, apakah di sini ada tempat atau kamar yang bisa disewakan?”
“Bukan, di kampung ini. Tapi yang murah. Hanya kamar. Satu kamar saja.”
“O, kalau di sekitar sini tidak ada Bu, agak jauh. Diujung sana. Mengapa ibu menanyakannya? Jangan bilang ibu ingin tinggal di tempat itu.”
“Tidak, untuk temanku. Besok aku mau jalan-jalan ke sana.”
Memang agak jauh, dan Rohana mendapatkannya. Tempat yang sederhana, dan bersih, tapi murah. Rohana membayarnya dengan uang yang dibawanya, kembalian dari pak Trimo si penjual nasi liwet.
Ketika sudah selesai, Rohana berhenti di sebuah pos penjagaan yang kosong, lalu menghitung sisa uangnya. Barangkali untuk perawatan Bejo masih diperlukan uang, sedangkan dia juga berjanji akan memberinya modal pada Kartinah agar mau berusaha untuk berjualan. Tidak mengemis seperti sebelumnya.
Tapi ketika ia sedang menghitung di depan pos penjagaan itu, seorang laki-laki lewat. Ia melihat uang, dan senyum licik tersungging di bibirnya. Dengan cekatan ia merebut setumpuk uang yang masih ada di pangkuan Rohana. Rohana terkejut. Tapi ia tak sudi mengalah. Ia pernah mengalaminya, dan tak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Tapi sekarang sudah berbeda. Matanya mencari sesuatu, dan melihat pentungan di pos penjagaan itu.
MASIH ADAKAH MAKNA 30
Pak Trimo dan Binari saling pandang, ini benar-benar uang, dan jumlahnya sepuluh juta? Bagaimana bu Rohana bisa mendapatkan uang sebanyak ini?
“Jangan-jangan ….” kata pak Trimo.
“Jangan-jangan dia mencuri, lalu diberikan kepada kita,” kata Binari cemas.
“Aduh, bagaimana orang itu?”
“Dia memberikan uang ini, kemudian bilang pada Bapak bahwa dialah yang mencuri uang Bapak waktu itu?”
“Iya. Tiba-tiba saja bilang begitu setelah memberikan amplop berisi uang itu. Dia juga bilang kalau dia akan mencari uang lagi yang akan diberikannya kepada kamu.”
“Jadi dia bermaksud mengganti uang yang telah dia curi? Tapi kalau dengan cara begini, apa itu benar?”
“Memang tidak benar. Sangat tidak benar. Kita tidak bisa menerimanya.”
“Lalu kita apakan uang ini Pak?”
"Simpan kembali di dalam amplop, jangan dipergunakan untuk apapun. Kalau dia datang lagi, kita kembalikan saja. Kita tidak bisa menerima uang yang tidak jelas dari mana datangnya.”
“Bapak benar. Baiklah, akan Binari simpan saja dulu uangnya. Atau dimasukkan ke bank saja?”
“Jangan. Kalau dimasukkan ke bank, nanti kalau dia datang sewaktu-waktu, susah mengembalikannya. Jadi simpan saja berikut amplopnya dan sembunyikan di tempat aman.”
“Binari, kamu harus segera mengabari nak Tegar tentang kedatangan bu Rohana, juga mengatakannya tentang uang ini.”
“Apakah kita juga akan mengatakan tentang pengakuan bu Rohana bahwa dia yang mencuri uang Bapak?”
“Bagaimana ya, apa tidak tersinggung mereka kalau kita mengatakannya?” rupanya pak Trimo masih ragu-ragu.
“Kita kan tidak menuduh. Kita hanya mengatakan apa yang dikatakan ibu Rohana.”
“Ya sudah, nanti gampang. Yang penting kamu kabari dulu saja nak Tegar tentang kedatangan neneknya, dan tentang pemberian uang ini.”
“Baik. Binari menyimpan uang ini dulu di dalam almari Binar ya Pak.”
Binari masuk ke kamar, kemudian menelpon Tegar, yang tentu saja kecewa karena Binari mengabari setelah Rohana pergi. Ia juga mengatakan bahwa ketika datang, wajah Rohana kelihatan terluka di beberapa bagian.
“Maaf Mas, tadi ketika bu Rohana datang, saya sedang pergi. Bapak tidak mampu menahannya karena kebetulan sedang banyak pembeli.”
“Tapi mengapa nenek memberikan amplop berisi uang itu.”
“Saya tidak mengerti jelasnya, atau bagaimana bu Rohana mendapatkan uang itu. Tapi setelah memberikan uang, bu Rohana mengatakan tentang sesuatu yang membuat kami terkejut.”
“Mengatakan apa dia?”
“Maaf Mas, jangan sampai Mas marah atau tersinggung, tapi memang inilah yang dikatakan ibu Rohana. Benar atau tidak, aku tidak tahu.”
“Iya, apa yang dikatakan nenek?”
“Bu Rohana mengatakan bahwa … bahwa … dialah yang telah mencuri uang bapak pada waktu itu.”
“Nenek mengatakan itu?”
“Iya. Bapak yang diberitahu tentang hal pencurian itu.”
“Jadi maksudnya … nenek memberikan uang itu untuk mengganti uang yang dicurinya?”
“Mungkin itulah maksudnya. Tapi kata bapak, kami tidak bisa menerimanya karena tidak jelas dari mana datangnya uang itu.”
“Benar, dari mana nenek mendapatkan uang sebanyak itu?”
“Uang itu masih kami simpan. Nanti kalau sewaktu-waktu bu Rohana datang, kami akan mengembalikannya.”
Binari menutup sambungan telpon. Tapi ia merasa lega sudah mengatakannya dan ternyata Tegar tidak kelihatan marah.
Satria juga terkejut mendengar cerita Tegar tentang Rohana yang mengaku mencuri uang pak Trimo dan menitipkan uang sebanyak sepuluh juta untuk menggantinya, atau mencicil menggantinya?
“Sepuluh juta itu banyak lho Mas,” kata Minar.
“Iya, dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu?”
“Aku takut Mas, jangan-jangan ibu melakukan hal yang tidak benar.”
Satria mengusap wajahnya, tak bisa menutupi kegelisahannya. Barangkali karena keadaan, lalu sang ibu melakukan hal-hal buruk.
“KIta tetap harus mencari ibu Mas, aku khawatir. Mengapa Binari juga mengatakan kalau wajah ibu kelihatan penuh luka,” kata Minar lagi.
Satria bertambah cemas membayangkan keadaan wajah ibunya yang penuh luka.
Setelah beberapa saat menenangkan diri, Satria segera memerintahkan kepada sang istri agar segera mengembalikan uang pak Trimo yang dicuri sang ibu.
“Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengembalikan uang pak Trimo yang telah diambil ibu.”
“Benar. Kasihan pak Trimo. Sudah berbulan berlalu, kita tidak tahu kalau ibu yang mengambilnya."
“Besok tanyakan pada pak Trimo, sebenarnya berapa banyak uang pak Trimo yang hilang.”
“Bagaimana dengan uang yang dari ibu?”
“Biarkan saja. Bukankah menurut Tegar, keluarga pak Trimo akan mengembalikannya? Mereka orang baik. Mana mau mereka menerima uang yang tak jelas dari mana. Aku yakin mereka juga berfikir bahwa ibu mendapatkan uang itu dengan jalan yang tidak benar,” kata Satria sedih.
“Ya sudah, untuk sementara kita selesaikan dulu urusan uang yang dicuri itu, dan kita akan menggantinya, berapapun jumlah uang itu. Dulu pak Trimo pernah mengatakannya, berapa banyaknya uang yang hilang. Tapi aku lupa.”
“Temui dia besok. Atau sebelumnya suruh Tegar menelpon Binari.”
“Aku ke sana saja, dan akan langsung memberikan uangnya.”
”Baiklah, terserah kamu saja.”
Tomy yang mendengar tentang ibunya juga merasa sangat gelisah. Mereka ketakutan kalau ibunya melakukan hal yang tidak benar. Uang sepuluh juta itu banyak. Dengan pekerjaan ibunya yang diketahuinya hanya menjadi pengelap kaca mobil-mobil, tidak mudah mendapatkan uang sebanyak itu.
Rasa khawatir itu membuat mereka semakin gigih dalam upaya mencari sang ibu. Mereka kembali melapor kepada polisi dengan mengatakan ciri-ciri sang ibu. Tapi tentu saja mereka tidak mengatakan tentang pencurian yang diakui sendiri olehnya itu.
Pak Drajat sedang kembali pulang ke luar Jawa, tapi berjanji akan segera mengurus pernikahan cucu-cucunya.
Pagi hari itu Kartika sedang bertelpon dengan seorang temannya, yang menceritakan tentang kelakuannya sendiri yang keterlaluan, karena menghajar wanita tua yang ternyata adalah orang yang menyelamatkan anaknya dari maut.
“Rina, kamu melakukannya? Kasihan dong, pasti dia terluka,” kata Kartika mencela kelakuan temannya yang bernama Rina.
“Ya ampun Tika, aku kalap waktu itu. Tiba-tiba Tony mengilang, aku tidak tahu dia pergi ke mana. Ee, tiba-tiba aku melihat Tony sedang menangis, didekap oleh wanita itu. Pikiran buruk aku muncul. Aku menduga wanita itu sedang membujuk Tony yang akan diculiknya.”
“Lalu bagaimana? Wanita tua itu marah dong?”
“Pastinya iya, aku memukulinya tanpa ampun. Berdosa aku ini Tika. Aku kemudian meminta maaf, dan memberi dia uang. Kamu tahu, aku baru saja mendapat uang muka pembayaran kontrak rumah aku yang disewa orang, sebanyak sepuluh juta. Masih utuh di dalam amplop. Lalu aku berikan semua uang itu padanya. Ini masalah nyawa anakku, uang sebegitu tak ada artinya.”
“Pasti wanita itu kemudian memaafkan kamu karena menerima uang itu.”
“Begitukah menurutmu?”
“Wanita itu mengembalikan amplopnya. Ia menolaknya kemudian berlalu.”
“Yaa Tuhan, dia orang baik ya Rin?”
“Jelas dia orang baik.”
“Senang dong kamu, duitmu utuh?”
“Tidak Tika, jangan seburuk itu kamu menilai aku. Aku kejar dia bersama Tony. Aku minta agar Tony mengucapkan terima kasih padanya.”
“Ia tampak tertegun mendengar Tony mengucapkan terima kasih. Saat itulah aku membantu Tony memasukkan amplop itu ke dalam tas keresek yang dia bawa, entah berisi apa.”
“Dia tetap menolaknya?”
“Aku langsung pergi sebelum mendengar dia menolaknya. Entahlah, aku tidak tahu kemudian diapakan uang itu.”
“Wah, memberikan uang di jalan ramai. Bagaimana kalau ada penjahat yang merampoknya?”
“Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu kelihatannya orang-orang baik. Mereka yang melihat kejadian di mana wanita tua itu menolong anakku, kemudian memaki-maki aku. Ia malah meminta agar wanita itu mau menerima amplop yang aku berikan.”
“Semoga saja ia bisa memanfaatkan uang itu.”
“Aamiin. Kalau aku tahu rumahnya, aku akan pergi ke sana dan meyakinkan diri aku bahwa uang itu bisa dimanfaatkannya untuk sesuatu yang berguna. Kelihatannya dia orang tak punya.”
“Penampilannya agak bersih. Mungkin dia miskin, tapi bukan pengemis. Entahlah. Sampai sekarang aku menyesal tidak menanyakan rumahnya.”
“Kamu sih, buru-buru pergi.”
“Kalau aku tidak buru-buru pergi, pasti dia akan mengembalikan uang itu lagi.”
“Semoga kamu bisa ketemu lagi pada suatu hari nanti.”
“Aamiin. Omong-omong, kapan Azka menikah? Teman-temannya sudah mendengar kalau dia mau menikah.”
“Oh, iya. Tapi masih beberapa waktu lagi. Masih menunggu kakak si gadis yang mau menikah lebih dulu. Saat ini aku sedang mau mencari pembantu nih.”
“Pembantu? Bukankah kamu lebih suka mengerjakan semuanya sendiri?”
“Aku dan suami aku masih harus membantu Azka di kantornya. Aku hanya ingin ada yang bersih-bersih rumah dan kebun. Itu saja.”
“Wah, mencari pembantu sekarang susah.”
“Benar. Tapi sudahlah, kapan kamu ke rumah, tapi kalau aku libur, seharian aku biasanya ada di kantor.”
“Kamu ini lagi di kantor?”
“Ya enggak, aku sudah pulang, tapi aku mau pergi belanja sebentar. Nanti kita ngobrol lagi ya”
Rohana sedang menyantap cemilan yang baru saja dibelinya. Entah mengapa, beberapa hari ini perasaannya terasa sangat ringan. Ia mencari makan dengan santai, dan perasaan tertekan yang menghantuinya sudah banyak berkurang. Barangkali karena dia telah memberikan uang yang di dapatnya setelah dia menolong seorang anak kecil. Atau barangkali juga karena dia telah mengakui perbuatannya mencuri kepada pak Trimo. Menurutnya setelah dia sadar, apa yang dilakukannya sangatlah membebani perasaannya. Berbuat kasar, menipu bahkan mencuri, terbawa dalam setiap langkah yang dilaluinya. Sekarang ia melangkah dengan ringan. Ia sudah berjanji kepada pak Trimo bahwa akan memberi uang lagi kalau rejekinya sudah terkumpul. Memang tidak mudah, tapi janji itu membuatnya bekerja lebih keras dan benar-benar menghemat pengeluarannya. Kesukaan makan enak yang digemarinya, sudah lama tak dilakukannya. Makan hanyalah sekedar saat dia lapar, dan tidak harus sesuatu yang membuat lidah menari.
Tiba-tiba ia mendengar sebuah mobil berhenti tak jauh di depannya. Ia meletakkan sisa cemilan di samping keresek yang selalu dibawanya, lalu mengambil lap sebagai alatnya bekerja.
Rohana bergegas menghampiri mobil itu, mengangguk kepada pengemudinya yang ternyata seorang wanita cantik, lalu ia memainkan lap yang dibawanya di kaca depan mobil itu.
Pengemudi mobil itu adalah Kartika. Entah mengapa Kartika menatap wanita yang sedang memainkan lap di kaca mobilnya. Kartika tahu bahwa kaca mobilnya sudah mengkilap, dan itu adalah cara seseorang untuk mencari uang.
Kartika merogoh tasnya karena merasa iba. Tapi ketika akan memanggilnya untuk diberinya uang, Kartika melihat beberapa luka yang belum mengering di wajah wanita itu. Diakah wanita yang telah menyelamatkan Tony, anak Rina yang nyaris tertabrak mobil?
Rohana yang tak merasa diawasi oleh mengemudi mobil, meneruskan pekerjaannya. Sekarang ia mengelap samping mobil itu.
Tiba-tiba Kartika membuka mobilnya, dan Rohana menyingkir minggir.
“Maaf Bu, kalau tidak berkenan,” kata Rohana sambil beranjak pergi.
“Tunggu Bu. Tidak apa-apa,” katanya sambil mengulurkan selembar uang dua puluhan ribu. Rohana mengamatinya, dan mengangguk sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih.
“Terima kasih Bu, ini sangat banyak.”
“Tidak apa-apa. Eh, tunggu dulu.”
“Apa ibu pernah menyelamatkan seorang anak kecil?” entah mengapa Kartika tertarik untuk menanyakannya.
“Oh, anak kecil itu. Namanya mirip anak saya. Terima kasih Bu,” Rohana beranjak untuk berlalu. Ia tak ingin ada orang yang mengungkit masalah itu, atau jangan-jangan wanita cantik itu saudara ibu galak yang telah menghajar wajahnya, lalu mau mengucapkan terima kasih lagi. Atau … jangan-jangan dia akan mengambil uang yang diberikan kepadanya karena menganggapnya terlalu banyak? Bermacam pemikiran itu membuat Rohana benar- benar kembali agar lebih jelas mengetahui apa keinginan si cantik itu.
“Siapa nama anak Ibu?”
“Tomy. Dia Tony. Ada apa ibu menghentikan saya? Kalau uang sepuluh juta itu terlalu banyak dan ibu akan mengambilnya, saya minta maaf, karena ….”
“Tidak, mengapa ibu berpikir bahwa saya berbicara tentang uang?”
“Barangkali ibu saudara dari wanita galak itu,” katanya lirih.
Kartika tersenyum. Wanita itu sangat jujur, dan timbullah rasa suka dihati Kartika.
“Bu, maukah ibu bekerja di rumah saya?”
MASIH ADAKAH MAKNA 35
Indira dan Azka menatap wanita tua yang mendekat sambil menunduk. Ia seperti menyembunyikan wajahnya, yang sembab dan tampak kuyu. Ia kemudian berjalan melalui pintu samping. Kartika berdiri, dan menyapa dengan khawatir.
Tapi Rohana terus melangkah. Kartika membalikkan tubuhnya, masuk ke dalam, bermaksud menemui nenek yang tampak sedang tidak seperti biasanya.
Mereka bertemu dari arah dapur. Kartika harus membukakan pintu belakang karena terkunci.
“Oh, maaf,” hanya itu yang dikatakan Rohana.
“Tidak apa-apa, masuklah.”
Rohana masuk lalu mengunci lagi pintunya.
“Apa yang terjadi?” kata Kartika yang kemudian mengambilkan segelas minum air putih yang diulurkannya kepada Rohana.
“Duduk dan minumlah Nek.”
“Terima kasih,” katanya. Ia kemudian meneguk minuman itu beberapa teguk. Tapi kemudian air matanya meleleh.
Kartika duduk di depannya. Membiarkan Rohana menenangkan hatinya dengan menangis.
“Dia sudah meninggal,” isaknya.
Kartika menatapnya iba. Jadi orang yang akan diberinya uang telah meninggal?
Rohana meletakkan sebuah kothak di meja dapur. Kartika belum menanyakan tentang kothak itu. Ia membiarkan Rohana sampai tangisnya mereda.
Rohana meneguk lagi air putihnya.
“Katakan ada apa, kalau Nenek sudah merasa tenang.”
”Maaf kalau saya terlambat kembali kemari.”
“Tidak apa-apa. Saya sudah menduga, pasti terjadi sesuatu pada Nenek. Tapi saya lega, Nenek pulang dengan selamat.”
“Teman saya tidak selamat.”
“Teman yang tadi Nenek datangin?”
“Tadi saya bertemu seseorang, dia anak teman saya, yang bernama Sofia. Saya heran dia masih mengingat saya. Dia bilang ibunya ingin bertemu saya, dan sudah sepuluh tahunan dia mencari keberadaan saya.”
“Rupanya dia sahabat lama Nenek?”
“Sebenarnya kami tidak begitu bersahabat. Dia memberikan ini ….”
Rohana menunjuk ke arah kotak kardus yang dibungkus kain batik.
“Ini adalah uang dua puluh juta, yang dulu dia pinjam dari saya. Padahal saya sudah melupakannya.”
“Jadi teman Nenek ingin bertemu Nenek, hanya untuk mengembalikan hutangnya kepada Nenek?”
“Keadaannya sudah buruk. Dia bercerita panjang dengan pelan karena tubuhnya lemah, lalu anaknya membawa dia ke rumah sakit. Saya mengikutinya, tapi kemudian dia meninggal.”
Rohana kembali terisak. Dengan terbata ia menceritakan pertemuannya dengan teman lamanya, sampai ketika dia mengantarkannya ke rumah sakit, dan menungguinya sampai dia meninggal.
“Begini rasanya kehilangan ….” tangisnya lagi.
Sementara itu Indira dan Azka masih berbincang di teras, tanpa tahu apa yang terjadi. Pratama, ayah Azka yang keluar, justru bertanya kepada mereka.
“Memangnya ada apa Pak?”
“Aku mendengar nenek menangis.”
“Menangis?” tanya Azka dan Indira hampir bersamaan.
“Ia bersama ibumu, nggak jelas apa yang dibicarakan, tapi aku mendengar nenek menangis.”
“Tadi juga ketika masuk seperti sudah tampak menunduk, wajahnya sembab,” kata Azka.
“Aku seperti pernah melihat wajah itu,” tiba-tiba kata Indira.
“Aku serumah, tapi hampir tidak pernah bertemu dia. Pagi sekali, minuman dan sarapan sudah tersedia, lalu aku dan bapak pergi ke kantor. Sore atau bahkan malam ketika pulang, ibu sudah menyuruhnya beristirahat. Sebulan di sini belum pernah bertegur sapa.”
“Kamu sibuk sekali, sih,” kata Indira.
“Aku sedang belajar. Jangan sampai mengecewakan Kakek.”
“Benar, Indira. Kelak, kalau kalian sudah menikah, semoga Azka sudah bisa menguasai semuanya sehingga tidak harus berada di kantor seharian. Dengan begitu akan banyak waktu luang untuk kamu,” kata Pratama.
Indira tertawa. Padahal Indira sendiri juga hampir seharian berada di kantor. Itu juga karena kakeknya.
Rupanya para pebisnis sudah mempersiapkan kelanjutan bisnisnya jauh-jauh hari kepada para keturunannya, agar kalau dia sudah tak ada, bisnis itu tetap berjalan sesuai yang diinginkan. Syukur-syukur bisa menjadi lebih besar.
“Tidak apa-apa Pak, selagi masih muda. Kakek saya juga berkata begitu kepada saya,” jawab Indira.
“Ini kok ada tamu tapi tidak dibuatkan minum sih?” tegur Pratama.
“Oh iya, biar aku ambilkan,” kata Azka sambil bangkit.
“Jangan, biar aku ambil sendiri saja,” sambung Indira yang juga segera berdiri.
Ketika sampai di dapur, Kartika sedang menyuruh nenek untuk beristirahat.
“Ya sudah, Nenek pasti lelah. Sekarang mandi dulu saja, dan istirahat. Nanti saatnya makan aku panggil Nenek. Ya.”
Rohana berdiri, lalu beranjak masuk ke dalam kamarnya.
“Uangnya ketinggalan, Nek.”
Rohana kembali, mengambil kotak pemberian Sofia yang memaksanya harus menerima uang itu.
Ketika Rohana berbalik, Azka dan Indira memasuki dapur.
“Eh, kalian? Aduh, ibu lupa membuatkan minum untuk kalian,” seru Kartika.
“Biar saya membuat minum sendiri, Bu.”
“Indi sedang belajar menjadi seorang ibu rumah tangga,” seloroh Azka.
“Oh, begitu? Baiklah. Silakan membuat minuman sendiri, ibu mau mandi.”
“Bu, Nenek tadi kenapa? Bukan karena kecelakaan, kan?” tanya Azka sebelum ibunya pergi.
“Hush. Kecelakaan apa. Dia itu sedih, menceritakan temannya yang tadi meninggal.”
“Dia pergi mengunjungi temannya?”
“Sebenarnya tidak. Dia hanya bertemu anaknya, yang mengatakan bahwa ibunya ingin bertemu Nenek. Ternyata itulah saat terakhir Nenek bertemu dengan temannya itu, jadi dia sedih sekali.”
“Ya sudah, buat minum dan cari cemilan sendiri, ibu mau mandi dulu. Bau acem …”
Tapi malam itu Rohana tak bisa tidur. Dia juga menolak untuk makan ketika Kartika membangunkannya. Hari itu adalah hari yang sangat buruk baginya. Dicurigai mendapatkan uang dengan jalan yang tidak benar, dan membuatnya menangis kesakitan karena hati terasa bagai dirajang-rajang. Lalu ia kehilangan seorang teman. Mereka tidak begitu dekat, hanya teman berhura-hura, tapi sang teman ternyata tidak melupakannya, hanya karena uang dua puluh juta yang pernah dipinjamnya. Padahal Rohana sudah melupakannya. Bukankah saat itu dia masih seorang wanita yang kaya raya?
Tapi melihat saat-saat Sofia menghembuskan napas terakhirnya, hatinya terasa pedih. Ia melihat kepergian yang tak akan mungkin bisa bertemu kembali. Ia merasa penyesalan demi penyesalan mengusik batinnya karena toh saat mati dia tidak akan membawa apapun juga. Hura-hura, kemewahan, gemerlapnya harta, apa yang terjadi sekarang? Sang teman sudah tak ada, dan apa yang dia miliki sekarang? Hanya sepotong tubuh dengan sedikit daging beselimut kulit keriput, dan selembar pakaian seadanya untuk menutupinya.
Rohana kembali menangis. Biarlah semuanya berlalu, bukankah sekarang dia ingin mendandani sisa hidupnya dengan banyak hal baik dan bersih dari noda dan dosa?
Rohana keluar dari kamar, menuju ke kamar mandi untuk berwudhu.
Doa-doa dan permohonan ampun yang mengalun bagai membubung ke ujung langit, yang semoga Allah subhanahu wata’ala mendengarnya.
Ketika ia terisak dalam pasrah dan penyesalan, Pratama sedang mau berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Suara aneh yang terdengar dari kamar Rohana membuatnya tertarik. Perlahan ia membukanya, yang kebetulan memang tidak terkunci, lalu ia terpana melihat Rohana sedang bersujut. Hati Pratama bergetar. Perlahan ia menutupkan lagi pintunya, lalu kembali ke kamar dengan rasa penuh penyesalan. Ia telah mencurigai Rohana selama ini, dan tidak mempercayai bahwa dia benar-benar orang baik. Malam itu, Pratama sadar bahwa dugaannya salah. Dalam hati ia berjanji akan lebih menghargai dan menghormati pembantunya yang tua itu, dan yang selalu hanya istrinya saja yang memberinya perhatian.
Pagi hari itu Rohana seperti biasa berkutat di dapur. Hampir semalaman dia tak bisa tidur, tapi dia tidak melupakan tugasnya untuk membuatkan minuman pagi untuk ‘majikannya’, sebelum bersih-bersih rumah ketika para ‘majikan’ sudah berangkat bekerja.
Ia sedang menuangkan segelas susu coklat ketika tiba-tiba Azka muncul.
“Nenek, minum untuk saya sudah ada? Saya mau keluar kota pagi-pagi.”
“Oh, iya, Tuan Muda. Tuan muda kalau mau coklat susu, ini sudah ada,” kata Rohana sambil meletakkan segelas coklat susu yang baru dituangnya.
“Iya Nenek. Tidak apa-apa. Saya tunggu di ruang makan ya.”
Rohana sudah mencuci wajahnya berkali-kali, tapi ternyata tidak bisa menghilangkan rona sembab yang melingkupi wajahnya.
Ia meletakkan nampan dengan segelas coklat di hadapan Azka.
“Nenek jangan memangggil saya ‘tuan muda’. Panggil saya Azka.”
Rohana hanya mengangguk. Ia tahu Azka sedang menatapnya.
“Wajah Nenek sangat pucat. Kalau sakit, istirahat saja dulu.”
“Lhoh, Azka sudah duluan ngopi nih,” kata Pratama yang sudah rapi juga. Keduanya akan pergi ke luar kota pagi-pagi.
“Ini Nenek membuatkan coklat susu untuk Azka.”
“Nenek, saya minta kopi pahit ya,” kata Pratama kepada Rohana yang sudah melangkah ke belakang.
“Baik,” jawabnya sambil menoleh sekilas.
Rohana selalu membuat minuman yang berbeda setiap pagi. Ada kopi pahit, ada coklat susu juga. Tapi dia tidak tahu, untuk siapa masing-masing minuman itu. Sekarang ia tahu, Azka dan Pratama lebih suka kopi. Berarti coklat susu itu untuk Kartika.
“Kelihatannya Nenek sakit,” kata Azka.
“Ya, tiba-tiba kasihan melihatnya,” jawab sang ayah yang kemudian duduk sambil menunggu kopi pahitnya.
“Beberapa kali Azka mengingatnya, seperti pernah ketemu Nenek, tapi lupa di mana.”
“Pastinya di jalanan. Bukankah ibumu ketemu dia di jalanan?”
“Iya Pak, pastinya sih.”
“Kalian mau sarapan apa?” tiba-tiba Kartika muncul dengan pakaian yang sudah rapi. Ia akan mengantar mereka ke bandara.
“Roti bakar saja,” kata Azka.
“Nggak usah, kita sarapan di bandara saja, takut terlambat,” sambung Pratama.
“Baiklah kalau begitu.”
Nenek membawakan kopi pahit pesanan Pratama, dan coklat susu untuk Kartika.
“Terima kasih Nenek. Kok Nenek kelihatan pucat. Habis ini istirahat saja di kamar, tidak usah mengerjakan apa-apa. Semua masih bersih kok.”
Rohana tersenyum tipis.
“Saya nanti setelah mengantarkan anak dan suami ke bandara, langsung ke kantor ya Nek, Nenek jangan lupa sarapan, makan siang. Pokoknya saat makan harus makan, tidak boleh sungkan.”
“Baik.” kata nenek sambil berlalu, tapi kemudian dia berhenti.
“Nanti saya akan takziah ke pemakaman teman saya, bolehkah?”
“Saya akan langsung ke pemakaman saja.”
“Baiklah, tapi Nenek hati-hati, dan kalau sudah selesai segera pulang ya,” kata Kartika.
“Baik,” katanya kemudian berlalu.
“Jangan lupa membawa payung Nek, ada di belakang. Udara sangat panas,” pesan Kartika. Rohana hanya mengangguk.
“Kasihan, nenek kelihatan sedih sekali setelah kehilangan temannya,” kata Kartika.
“Lewat tengah malam aku melihatnya shalat sambil menangis.”
“Wajahnya sampai pucat begitu. Barangkali dia tidak tidur semalaman.”
“Aku seperti pernah melihat wajah seperti nenek itu,” kata Azka sambil menghabiskan coklat susunya.
“Kamu sudah mengatakannya berkali-kali,” kata Kartika.
“Ya, tadi juga mengatakannya lagi.”
“Ayo, nanti terlambat, segera siap-siap. Mana yang harus dibawa,” kata Kartika mengingatkan.
“Sudah Azka siapkan semuanya, ibu tidak usah khawatir,” kata Azka.
Tomy sedang sarapan pagi, menikmati sepotong pisang goreng sambil membuka-buka koran pagi. Tiba-tiba ia melihat sebuah kolom berita duka.
“Apa ini bukan teman ibu ya?” serunya.
“Ini, meninggal kemarin sore, dimakamkan nanti siang. Namanya Sofia Andarini. Ini seperti nama teman ibu.”
“Belum tentu juga kan Mas, nama bisa saja sama.”
“Dulu rumahnya dekat kantor bapak, tapi nggak tahu sekarang alamatnya beda.”
“Apa Mas akan melayat ke sana?”
“Kalau tempat pemakamannya sih tiap hari aku lewat, nanti aku tanyakan, apa benar dia. Aku sih tidak begitu kenal, cuma saja ada pemikiran, jangan-jangan ibu mendengar berita ini dan ikut melayat di sana.”
“Wah, kalau begitu Mas perlu datang melayat. Semoga bisa bertemu ibu.”
“Semoga ibu mendengarnya dan ingin mengantarkan temannya ke peristirahatannya yang terakhir.”
“Kalau begitu Mas harus cepat-cepat mencari tahu tentang dia.”
“Barangkali benar dia, salah seorang anaknya Lukman, dia pelukis. Nih dia ada tertulis di sini. Nanti aku akan ke pemakamannya saja.”
Panas begitu terik. Rohana datang ke pemakaman Sofia dengan membawa payung. Banyak pelayat yang datang. Rohana melihat peti berhiaskan bunga-bunga mulai diturunkan ke liang lahat. Mulutnya berkomat-kamit membacakan doa, dengan air mata merebak di pelupuknya.
Sampai acara pemakaman selesai, Rohana masih tegak di sana. Ia menaburkan bunga yang dibelinya sendiri.
'Selamat jalan, Sofia. Uang darimu akan aku pergunakan untuk sesuatu yang berguna, agar menjadi bekal amalmu di sana.’
Rohana melangkah perlahan untuk meninggalkan pemakaman. Ia meraih payungnya yang semula diletakkan di tanah, tapi kakinya tersandung batu. Sepasang tangan merengkuhnya, dan membantunya berdiri. Lalu mereka saling pandang dengan perasaan heran.
MASIH ADAKAH MAKNA 34
Rohana terus melangkah. Hatinya serasa diiris dengan ribuan sembilu. Ternyata sebuah usaha baik masih menimbulkan prasangka. Ternyata keinginannya untuk menjadi baik tidak membuat orang percaya. Iya lah, seorang peminta-minta, atau seorang yang hidup di jalanan, kemudian memiliki uang sepuluh juta untuk membayar ‘hutang’? Walau ia bisa menerima perlakuan itu, tapi rasa sakit itu membuat air matanya tak berhenti bergulir.
Tadi ia berpamit kepada ‘majikannya’ untuk membayarkan uang gajinya demi menambah ‘cicilan hutangnya’ kepada pak Trimo. Tapi suara pak Trimo, orang yang selama ini selalu bersikap baik padanya, ternyata sangat membuatnya sakit. Ia membawa uang gajinya kembali, karena bagaimanapun pasti dikiranya uang itu dari hasil yang tidak benar.
Sambil mengusap air matanya, ia menunggu angkutan kota untuk menuju ke rumah keluarga Pratama kembali.
Tapi tiba-tiba seorang pengendara motor berhenti tepat di depannya, sehingga menghentikan langkahnya.
Rohana menatapnya tak berkedip. Wajah itu serasa pernah dikenalnya, tapi ia lupa di mana. Tapi pengendara sepeda motor itu rupanya mengenalinya.
Rohana mencoba mengingat-ingat, kapan pernah bertemu laki-laki itu. Ia bukan lagi seorang anak muda. Umurnya pastilah di atas 40 an tahun. Tapi wajahnya yang bersih, walau tidak terlalu tampan, tampak seperti seseorang yang berhati baik. Kalaupun dia penjahat, untuk apa menjahati perempuan tua yang miskin seperti dirinya?
“Ibu pasti lupa pada saya. Dulu, waktu bu Rohana sering bepergian bersama ibu saya, saya masih remaja.”
Rohana harus memeras otaknya untuk mengingat-ingat. Air mata di wajahnya sudah mengering, karena sengatan matahari yang cukup panas.
“Ibu Rohana ingat ibu saya, namanya Sofia.”
Rohana terhenyak. Sofia adalah temannya berhura-hura di masa itu. Pada suatu hari Sofia berhutang padanya sebanyak dua puluh juta, lalu kabur, dan tak pernah kembali ke kelompok hura-huranya lagi. Waktu itu uang Rohana masih berlimpah. Kehilangan duapuluh juta tidak pernah dipikirkannya. Ia juga lupa tentang uang yang dibawa kabur Sofia.
“Ini wajah ibu saya ketika masih agak muda,” laki-laki itu menunjukkan sebuah wajah di layar ponselnya. Rohana tidak melupakannya.
“Sejak sepuluh tahun yang lalu, ibu saya mencari-cari Ibu. Saya tadi mengingat-ingat wajah Ibu, yang walaupun sudah jauh lebih tua, tapi tidak pernah saya lupakan. Ibu masih mirip puluhan tahun yang lalu, walau penampilan Ibu berbeda."
“Oh ya? Kamu itu kan yang sering mengantar Sofia dengan mobil antik itu? Kamu kan yang suka melukis? Bahkan kamu pernah melukis wajahku?”
“Aku ingat, Lukman. Sekarang apa kabar Sofia?”
“Itulah Bu. Sekarang ibu sudah sakit-sakitan. Tadinya di rumah sakit, tapi karena biaya membengkak, ibu minta di rawat di rumah. Ibu selalu menyebut-nyebut nama ibu Rohana. Katanya ia merasa bersalah.”
“Ah, tidak. Semua orang pasti pernah melakukan salah.”
“Maukah Ibu menemui ibu saya?”
“Bagaimana kamu bisa mengenali wajahku, yang sudah jauh lebih tua, beda penampilan juga. Karena aku sekarang miskin, papa,” kata Rohana dengan wajah sendu.
“Saya pernah melukis wajah ibu Rohana. Saat muda, dan bagaimana nanti setelah tua. Dulu ibu Rohana sangat cantik. Lihat, saya melukis wajah Ibu saat tua. Hanya bedanya lukisan ini tidak memakai jilbab.”
Rohana terbelalak melihat wajahnya pada lukisan yang terpampang di ponsel Lukman. Itu memang dirinya saat sekarang. Senyumnya mengembang. Lukman memang pelukis yang hebat.
“Ibu, ibu saya pasti senang kalau bisa bertemu Ibu. Katanya ia merasa bersalah, tapi saya tidak tahu apa kesalahan yang ibu saya perbuat pada Ibu.”
“Di mana ibu kamu tinggal?”
“Tidak jauh dari sini, ibu berani membonceng sepeda motor saya?”
“Baiklah, tapi saya tidak bisa lama, karena saya bekerja di sebuah rumah dan harus segera kembali.”
“Saya belum mendengar bagaimana ceritanya sehingga Ibu seperti ini. Tapi yang penting Ibu menemui ibu saya dulu. Dia sakit parah.”
“Baiklah, ayo kita temui dia.”
Rasa hati Rohana sudah berbeda, Dulu, barangkali dia tidak akan peduli kepada derita orang lain. Tapi sekarang dia sudah berbeda. Mendengar kisah Sofia yang sakit-sakitan, jatuh rasa iba dihatinya. Karenanya dia bersedia mengikuti Lukman untuk menemui teman lamanya.
Ketika Binari kembali ke warung dengan membawa amplop yang dulu diberikan Rohana, ia tak melihat Rohana ada di sana. Tegar sedang berbincang dengan ayahnya, yang merasa menyesal karena Rohana tak mau dihentikannya.
“Memang susah Nak, bu Rohana sama sekali tidak mau berhenti. Tampaknya dia juga marah ketika saya mau mengembalikan uang yang dulu diberikannya.”
“Iya Pak, saya bisa mengerti. Jarak dari warung ini dan tempat saya berada tidak bisa diprediksi akan berapa lama bisa sampai lalu bertemu dengannya, sedangkan nenek selalu pergi dengan tergesa-gesa.”
“Saya minta maaf, Nak. Mau bagaimana lagi? Bu Rohana bukan anak kecil, dan tidak mungkin saya mengikatnya sehingga dia tidak bisa pergi.”
“Ya sudah. Tidak apa-apa. Barangkali memang belum saatnya saya bisa bertemu nenek. Tapi saya masih akan mencoba, barangkali bisa bertemu di daerah ini.”
“Tadi saya juga sudah secepatnya memberi tahu Mas, begitu dia datang,” kata Binari.
“Aku masih ada di kampus, dan aku juga ngebut tadi.”
“Lain kali tidak usah ngebut, jalanan ramai lho Mas. Tapi menyesal juga aku, tidak bisa mempertemukan Mas dengan bu Rohana. Padahal beberapa kali dia datang kemari.”
“Bu Rohana sangat sulit. Dia selalu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kalau saja tadi dia mau berhenti dan saya suguhkan makan, barangkali Nak Tegar masih bisa bertemu. Tapi karena terbawa perasaan marah, jadi ia sama sekali tidak mau mendengar perkataan saya," kata pak Trimo.
“Mengapa dia marah ya Pak?”
“Gara-gara saya mau mengembalikan uangnya. Saya malah tidak sempat memberi tahu bahwa bu Satria sudah memberi saya uang.”
“Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu, semoga saya bisa melihat nenek di sekitar tempat ini.”
“Tidak mau makan dulu Mas?”
“Terima kasih Binari, lain kali saya pasti akan sarapan di sini sebelum kuliah.”
Binari tersenyum. Tegar menatapnya kagum. Ketika memakai hijab, Binari tampak lebih cantik. Ia tak butuh melihat ekor kuda yang selalu membuatnya merasa lucu. Yang ini lebih menawan.
Tegar mengibaskan perasaan aneh yang selalu mengganggunya setiap kali bertemu Binari, kemudian berlalu.
Rohana terkejut melihat sosok wanita tua yang terbaring tak berdaya. Wajahnya yang penuh keriput tampak tak bercahaya. Ia menatap Rohana tak percaya, setelah Lukman mengatakan bahwa dia adalah memang Rohana.
“Sofia, kamu tidak mengenali aku lagi?” kata Rohana sambil duduk di kursi yang disediakan di samping tempat tidur Sofia. Tempat tidur sederhana, jauh dari kemewahan seperti dulu ketika mereka masih berteman.
“Kamu … benarkah kamu Rohana?”
“Tentu saja. Kita masih berteman, bukan?”
Rohana terkekeh. Dia sudah merasa tua, dan akhir-akhir ini tak ingin berdandan lagi. Ia tahu Sofia hanya ingin menyenangkan hatinya.
“Sudah lama aku ingin bertemu denganmu, Rohana. Sebelum aku mati, aku harus bertemu dan mengembalikan uang yang dulu pernah aku pinjam," katanya pelan, seperti tak mampu mengeluarkan suara keras.
“Kamu mengatakan apa? Jangan bicara tentang kematian.”
“Aku sudah tua, dan sudah lama sakit. Lukman, ambilkan kotak di dalam kantung batik yang ada di dalam almariku,” perintahnya kemudian kepada Lukman.
Lukman segera pergi untuk menuruti perintah sang ibu, sementara seorang pelayan menyuguhkan secangkir kopi di atas meja, di dekat Rohana duduk.
“Ini rumah Lukman. Dia masih terus melukis, istrinya bekerja. Mereka hidup sederhana.”
Lalu Sofia menghela napas sedih.
"Harta itu tidak bisa menjamin kesejahteraan seseorang untuk selamanya. Kemewahan yang dulu membuat aku berkecimpung dalam lautan kesenangan, sudah sirna. Semuanya habis, setelah usaha suamiku bangkrut. Aku tidak bisa membayar hutangku kepadamu, lalu pergi menyembunyikan diri di tempat terpencil. Tapi Lukman menjemputku, mengajaknya hidup sederhana bersama keluarganya,” katanya panjang lebar, disertai napas yang terkadang memburu.
“Kamu jangan memikirkan hutang itu lagi, aku sudah melupakannya.”
“Tidak, hutang itu membebani aku. Aku mengumpulkan uang yang aku simpan, menunggu saat bertemu denganmu. Jangan sampai kalau aku mati sewaktu-waktu, hutang itu menghambat jalanku.”
“Sofia, kamu belum akan mati. Sembuhlah dan nikmati hidup ini. Aku juga bukan seperti dulu. Hartaku habis dan aku terlunta-lunta puluhan tahun. Aku tak ingin membebani anakku, dan sekarang aku bekerja menjadi pembantu di sebuah keluarga.”
“Memangnya kenapa? Aku sudah menikmati hidupku, lalu merusak hidupku, dan sekarang aku sedang mendandani hidupku.”
Sofia tampak terengah-engah. Ia sudah banyak bicara, dan lelah. Ketika Lukman datang dan membawa kotak yang dipesankan ibunya, Sofia menerimanya dengan tangan gemetar.
“Rohana, ini uang yang aku kumpulkan, uang kamu yang pernah aku pinjam,” katanya sedikit terengah. Tangan yang terulur tampak gemetar, dan Rohana dengan segera menerimanya.
“Ibu istirahat dulu saja,” kata Lukman yang cemas melihat wajah ibunya.
“Lukman, aku senang sudah bertemu Rohana,” katanya lagi.
“Sofia, ini tidak perlu. Kamu pasti memerlukannya untuk berobat. Aku tidak membutuhkannya.”
“Jangan, tak ada yang bisa mengobati. Aku menderita kanker yang sudah parah. Aku hanya menunggu bertemu kamu,” lalu Sofia memejamkan mata.
Rohana ketakutan. Wajah itu seperti kehilangan cahayanya.
“Lukman, bawa ibumu ke rumah sakit,” kata Rohana panik.
Lukman segera menelpon rumah sakit untuk meminta ambulans bagi ibunya.
Kartika sudah sampai di rumah, tapi dia tidak menemukan nenek Rohana. Semuanya tampak rapi, tak ada yang mencurigakan, tapi Pratama tak mau mempercayainya, Ia menuduh Rohana telah melakukan hal yang tidak benar.
“Coba periksa kamar kamu. Almari kamu. Jangan mudah percaya begitu saja,”
“Mas, dia sudah bekerja sebulan lebih, dan semuanya baik-baik saja. Kita tidak pantas mencurigainya.”
“Coba saja periksa kamar. Orang jahat selalu melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Ia melakukan hal baik selama sebulan, untuk membangun kepercayaan kita. Lalu setelahnya ….?”
Kartika masuk ke kamar dengan kesal. Ia tak suka suaminya menuduh Rohana melakukan hal buruk. Kamarnya masih rapi. Almari masih terkunci.
“Coba buka dulu, dan periksa barangkali ada yang hilang,” kata Pratama yang menyusul masuk ke dalam kamar.
Kartika membuka almari, semuanya rapi.
“Periksa kotak perhiasan,” titahnya lagi.
Tapi semuanya masih seperti semula. Kartika mengangkat kedua belah tangannya untuk meyakinkan suaminya bahwa tak ada yang berubah, tak ada yang hilang.
“Apa lagi yang harus diperiksa?”
Tak terima, Pratama juga membuka almarinya sendiri. Tapi memang Rohana tidak melakukan hal buruk di rumah itu. Seisi rumah diperiksapun juga tak ada yang berubah. Semuanya rapi, dan bersih. Rupanya sebelum pergi Rohana telah membersihkan rumah dan melakukan apa yang menjadi tugasnya.
“Tadi nenek pamit mau pergi sebentar untuk menemui seorang kenalannya. Kalau tidak salah akan menitipkan uang gajinya, untuk dibayarkan kepada temannya itu,” kata Kartika yang tidak mau menyebut soal pencurian yang pernah dilakukan Rohana.
“Kenapa kalau bilang sebentar, lalu sampai sore dan hampir malam dia belum juga kembali?”
“Barangkali ada sesuatu, atau jangan-jangan terjadi sesuatu yang … aduh, mengapa dia tidak punya ponsel sehingga aku tidak bisa menghubunginya? Aku justru mengkhawatirkannya.”
“Kamu berlebihan, Kartika.”
“Sungguh, perasaanku jadi tidak enak.”
“Tungguin saja dulu, aku mau mandi,” kata Pratama yang tidak setuju sang istri begitu panik memikirkan nenek.
Tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Rupanya Azka datang sambil mengajak Indira.
Kartika menyambut di teras sambil tersenyum ramah.
“Indira, lama tidak bertemu kamu.”
“Iya Bu, setelah dulu kemari dan tidak bertemu Ibu, lalu belum datang kemari lagi,” kata Indira sambil mencium tangan Kartika.
“Itu sebabnya Azka tadi menjemputnya di kantor, Bu,” sambung Azka.
“Ayo masuklah,” ajak Kartika ramah.
“Kok ibu ada di depan? Bukan nungguin Azka kan?” kata Azka sekenanya.
“Memang bukan. Ibu sedang nungguin nenek.”
“Memangnya nenek ke mana?”
“Tadi siang pamit mau menemui temannya, kok sampai sekarang belum kembali,” kata Kartika yang kemudian menemani duduk tamunya di teras.
Tapi tiba-tiba sebuah taksi berhenti, dan Rohana turun dari sana dengan wajah menunduk.
MASIH ADAKAH MAKNA 40
Laki-laki penyerobot uang Rohana itu menatap Rohana dengan pandangan meremehkan. Hanya seorang perempuan tua, lagipula di sekitar tempat itu kelihatan sepi. Ia melenggang seenaknya, sebelum kemudian berbelok ke arah jalan kecil kemudian bermaksud menghilang.
Tapi Rohana bukan wanita lemah. Kemarahannya memuncak, karena sisa uang untuk mengentaskan seorang miskin telah dirampas. Ia meraih pentungan yang ada di pos penjagaan itu dan mengejarnya dengan kekuatan yang tidak wajar, karena diiringi oleh rasa marah yang membakar seluruh aliran darahnya. Dua langkah lagi dia sudah sampai di belakang laki-laki itu dan mengayunkan pentungan ke arah kepalanya, tapi luput karena laki-laki itu lebih tinggi. Hanya mengenai pundaknya, tapi cukup membuat laki-laki itu tersungkur.
Rohana berteriak sekeras-kerasnya.
“Maliiiiiiiing …. maliiiing …. “
Uang yang tadinya berada dalam dekapan laki-laki jahat itu berhamburan di tanah, dan laki-laki itu belum mampu bangkit karena sebelah bahunya terasa sakit. Jeritan Rohana membuat beberapa orang keluar.
Rohana terus berteriak dengan masih memegangi pentungan. Ia ingin mengayunkan pentungan itu lagi, tapi maling keparat itu sudah mampu bangkit. Ia menarik pentungan Rohana dan bermaksud membalasnya dengan ganas. Ia berhasil, lalu memukul lengan kiri Rohana dengan pentungan yang sudah dipegangnya, lalu ingin memukul kepalanya juga. Tapi dari belakang beberapa orang sudah mendekat dan memukuli tubuhnya dengan bertubi-tubi. Si maling kembali jatuh, tapi kemudian bangkit dengan ketakutan. Ia memilih mengambil langkah seribu sebelum tubuhnya remuk dihajar masa.
Rohana berjongkok memunguti uangnya, dan memasukkannya ke dalam tas kembali. Lengan kirinya terasa nyeri, tapi tidak dirasakannya.
Beberapa orang berusaha mengejar si penjahat, beberapa lagi mendekati Rohana.
“Nenek tidak apa-apa?”
Rohana bangkit dan tersenyum.
“Tidak, untunglah kalian datang. Kalau tidak, barangkali ia berhasil meremukkan tulang tuaku ini. Terima kasih banyak.”
“Lain kali Nenek harus berhati-hati. Orang jahat berkeliaran di mana-mana.”
“Iya, baiklah,” kata Rohana kemudian berlalu sambil memegangi lengan sebelah kirinya yang terasa sangat nyeri, karena terkena pentungan dari penjahat itu.
Rohana sudah sampai di rumah sakit kembali. Ia puas bisa mendapatkan tempat sederhana yang cukup nyaman untuk Kartinah dan anaknya. Ia juga membeli alas tidur dan beberapa perlengkapan untuk kebutuhan sehari-hari, yang ia tahu bagaimana cara memesannya. Kartinah akan bisa memasak dan menyimpan barang-barangnya di almari plastik yang disiapkan semuanya oleh Rohana. Ketika ia menemui Kartinah di ruang rawat Bejo, dilihatnya Kartinah tampak termenung sambil memegangi lembaran kertas yang diberikan perawat, sebagai tagihan atas beaya selama empat hari Bejo dirawat, dan obat-obat yang diberikan oleh rumah sakit.
Bejo duduk di tepi ranjang, sambil memegangi sepotong roti, sisa kemarin sore, di mana Rohana membelikannya.
“Bejo sudah sehat?” tanya Rohana.
“Hari ini boleh pulang. Tapi ….”
“Tapi apa, uangnya kurang?”
Kartinah tak menjawab. Rohana mengambil kertas yang dipegang Kartinah, dan bergegas pergi ke ruang administrasi.
“Nenek Rohana,” panggil Kartinah.
“Tunggu di situ, aku segera kembali,” kata Rohana yang kemudian menghilang di balik korden pembatas pasien yang ada di ruangan itu.
Kartinah memeluk anaknya dengan linangan air mata.
“Bejo, kamu hidup karena nenek yang baik hati itu. Kata nenek, ini karunia Allah. Kita harus berterima kasih kepadaNya. Mulai sekarang kita tidak boleh melupakanNya. Dan kamu harus belajar menjadi anak soleh, yang mengerti tentang kasih sayangNya. Ya?”
Bejo menatap ibunya sambil menggigit sisa rotinya, tapi si kecil itu seperti mengerti perkataan yang didengarnya. Ia mengangguk, dan sang ibu memeluknya.
“Baju Bejo … baru ya Bu?”
“Iya. Kamu punya beberapa baju baru. Kamu ganteng dan tidak kotor seperti dulu.”
Kartinah mengemasi barang-barangnya.
“Kita akan jalan-jalan lagi?” tanya si kecil.
“Nenek Rohana melarang kita menjadi peminta-minta. Ibu akan berjualan. Entahlah, apa nanti yang bisa ibu lakukan,” kata Kartinah seakan mengira bahwa sang anak mengerti apa yang dikatakannya. Entahlah, Rohana juga belum mengatakan apa-apa tentang keinginannya itu.
Ketika Rohana kembali, ia menyerahkan berkas dari rumah sakit yang sudah bertanda lunas. Kartinah ingin menjatuhkan tubuhnya di hadapan Rohana, tapi Rohana mengangkatnya.
“Apa yang akan kamu lakukan?”
“Apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Nenek? Saya bersedia menjadi pelayan Nenek dan melayani semua kebutuhan Nenek.”
“Apa? Aku tidak butuh pelayan. Kamu pikir aku seorang nyonya besar? Ayo kita pulang, aku tunjukkan tempat tinggal yang nyaman untuk kalian, dan tempat yang bagus untuk kamu berjualan.”
Rohana membantu Kartinah membawa tas berisi barang-barangnya, lalu menariknya keluar. Kartinah menggandeng tangan Bejo yang sudah bisa berjalan dengan lincah.
Kartinah kembali menangis haru sambil memeluk Rohana, ketika mereka sudah sampai di tempat yang disewa Rohana.
"Hentikan tangismu. Lihat, anakmu berbaring nyaman di tempat tidur itu. Ia pasti heran melihat ibunya selalu menangis."
“Ini rumah Nenek?” tanya Bejo sambil tiduran.
“Ini rumah Bejo,” jawab Rohana.
“Ya, sekarang kamu tidur di sini, makan di sini, dan mandi setiap pagi dan sore, supaya wangi.”
Bejo menatap ibunya, tak percaya, matanya berbinar ketika melihat sang ibu mengangguk.
“Kamar ini sudah aku bayar selama setengah tahun. Ini uang untuk kamu. Pakailah untuk berdagang, apa saja. Jangan sampai kamu dan anakmu tidak makan lalu kembali menjadi peminta-minta,” kata Rohana sambil memberikan sejumlah uang.
“Nenek Rohana, Nenek telah membuat kami menjadi orang yang sebenar-benarnya orang. Semuanya karunia bagi saya dan Bejo. Saya pasti akan menjalankan amanah yang Nenek berikan."
“Ingat. Setelah setengah tahun kamu harus bisa melanjutkan pembayaran sewa kamar ini. Kamu tahu caranya bukan? Uang harus diputar. Bagaimana pula caranya? Jadikan sebagai modal usaha. Tidak seberapa, kecil-kecilan saja, kalau kamu tekun pasti akan menjadi besar. Pada suatu hari nanti, ketika aku melihat kalian lagi, aku berharap kamu sudah bisa berdiri tegak, dan satu lagi, jangan sampai anakmu tidak sekolah.”
Kartinah yang tak lagi bisa menjawabnya karena haru yang menyesak, hanya mengangguk-angguk, lalu memeluk Rohana erat.
“Aku kan sudah bilang, jangan menangis,” kata Rohana yang kemudian berlalu dengan air mata yang tak urung juga membasahi pelupuknya. Dalam hati dia bersyukur, bisa melakukan hal yang dianggapnya sangat luar biasa. Hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, berbuat sesuatu untuk kehidupan seseorang.
“Ya Allah, terima kasih,” bisiknya sambil menunggu angkot untuk membawanya pulang.
Ketika itu ponselnya berdering, dengan kesal Rohana mengangkatnya.
“Bukankah aku sudah bilang kalau ponsel ini hanya mengganggu?” omelnya, tapi ia tetap mengangkatnya. Dari Monik.
“Ibu ada di mana? Ramai sekali, di jalan ya?”
“Kamu bertanya tapi sudah menjawabnya sendiri,” kesal Rohana.
“Ibu, apakah ibu sudah mau pulang?”
“Ini mau pulang. Apa kamu memasak urap daun kenikir dan layur goreng seperti pesananku?”
“Iya bu, ini sudah selesai. Apa di dekat ibu ada warung yang menjual gado-gado?”
“Gado-gado? Tidak ada. Apa kamu ngidam?”
“Ya enggak lah Bu, hanya ingin saja. Sekarang ibu cepat pulang ya, Monik sendirian nih.”
Tapi ucapan gado-gado yang didengarnya, membuat Rohana mendapat ide yang dianggapnya lumayan. Tak ada yang jual gado-gado di sekitar tempat itu. Ia bergegas kembali ke tempat di mana Kartinah berada, lalu menawarkan usulan untuk berjualan gado-gado.
Rohana pulang dengan wajah berseri-seri. Tiba-tiba dia juga ingin gado-gado. Tapi bagaimana membuat gado-gado? Selama hidup Rohana tidak suka memasak, jadi sudah pasti tidak bisa. Diangkatnya ponselnya untuk menelpon Minar. Bukankah menantunya yang satu itu juga pintar memasak? Akhirnya Rohana mengerti, ternyata ponsel yang sering membuatnya mengomel ada juga gunanya.
Ketika ia harus naik ke dalam angkot, tiba-tiba ia merasa kedua lengannya nyeri, apalagi yang sebelah kiri. Tapi kemudian ia mengacuhkannya.
Ketika Rohana sampai di rumah Tomy, ia melihat ada beberapa orang sedang ada di paviliun. Mereka mengukur dan keluar masuk sambil mencatat entah apa yang dicatatnya. Monik ada di teras, Rohana menghampirinya.
”Siapa mereka? Apa paviliun itu mau disewakan?” tanya Rohana.
“Tidak Bu, bapak menyuruh membenahi paviliun itu agar lebih baik.”
“Untuk apa? Maksudmu nanti kalau Boy sudah menikah, kamu akan menyuruhnya tinggal di situ?”
“Tidak. Boy sudah punya rumah sendiri. Paviliun itu untuk ibu.”
“Kata bapak, Ibu lebih baik tinggal di paviliun itu, supaya ibu merasa lebih nyaman, sehingga bisa melakukan apa saja yang ibu sukai. Nanti Monik yang akan melayani semua kebutuhan Ibu.”
“Tidak, jangan lanjutkan. Aku tidak mau diperlakukan lebih. Aku akan tidur di kamar mana saja, jangan membuat aku sungkan dan merasa merepotkan.”
“Mengapa Ibu merasa sungkan? Ini juga rumah Ibu, bukan?”
“Tapi jangan perlakukan aku seperti itu. Aku bukan orang yang harus dilayani khusus, aku lebih suka yang sederhana, jangan berlebihan,” katanya sambil melangkah masuk. Monik mengikutinya.
“Bu, bapak yang meminta itu, kami tak bisa menolaknya.”
“Bilang pada ayah mertuamu itu, aku tidak mau.”
Rohana masuk ke dalam kamar, membersihkan diri dan menggantikan pakaian rumah.
“Besok bapak sudah mau pulang. Nanti Ibu bilang sendiri saja pada Bapak,” kata Monik ketika mereka sudah duduk berdua di ruang makan.
"Besok aku mau ke rumah Satria.”
“Tidak, aku sudah pesan gado-gado pada Minar, besok dia akan membuatnya.”
“Haaa, gado-gado itu kan yang pengin Monik? Ibu pesan sama Minar?”
“Kalau begitu besok Monik antar Ibu ke rumah Minar, Monik juga mau gado-gadonya. Benar, Minar pasti bisa, Monik akan belajar dari dia.”
“Mertua kamu mau pulang, masa kamu malah pergi?”
“Tidak apa-apa, kita perginya pagi. Bapak pulang siang, agak sore, menunggu dijemput mas Tomy."
Minar senang sekali ketika ibu mertuanya datang. Ia sudah belanja masakan pesanannya sejak sang ibu menelponnya kemarin. Ia hanya membeli sambal pecel tinggal membumbuinya, dan beli sayuran untuk gado-gado Solo.
“Ibu kan mau tinggal di sini? Kamar sudah Minar siapkan, seperti kamar ibu yang dulu. Ini barang-barang Ibu?” kata Minar sambil membawa tas Rohana yang berisi pakaian, dibawanya masuk.
“Minar, apa kamu sudah selesai masak gado-gadonya? Biar aku bantu kamu memasaknya. Sambil belajar nih,” kata Monik ketika mereka sudah duduk bersama.
“Aku buat gado-gadonya sederhana saja kok.”
“Bukankah harus menumbuk kacang, segala macam?”
“Tidak usah. Aku buat yang sederhana saja kok.”
“Sederhana bagaimana? Nggak pakai kacang, gitu?”
“Eeeh, bukan. Ya pakai. Tapi aku beli sambal pecel yang sudah jadi.”
“Namanya sayur pecel dong, bukan gado-gado.”
“Ya bukan. Sambal pecel itu dilumatkan, dan masih dibumbui juga. Tambahkan bawang putih, sama santan, dan garam juga. Tambahin lagi daun jeruk purut, biar sedap. Lalu icipin, mana yang kurang. Sudah jadi gado-gadonya.”
“Oo, gitu ya? Besok mau nyobain deh.”
“Sekarang saja dicobain rasanya. Ayo Bu, kita makan gado-gado,” ajak Minar sambil menggandeng sang ibu mertua.
Tapi Rohana tampak meringis kesakitan. Lengan kirinya terasa sakit sekali.
“Lenganku sakit sekali. Kemarin tidak apa-apa, atau tidak begitu terasa, tapi sekarang rasanya sangat nyeri.”
“Memangnya ibu kenapa? Habis jatuh?” tanya Monik yang kemudian menyingsingkan lengan baju ibunya.
“Aduuh, mengapa kamu memijitnya keras?”
“Ini kenapa Bu? Sampai matang biru begini?”
“Dipukul orang. Kemarin belum terasa sih.”
“Dipukul orang?” pekik Minar dan Monik hampir bersama-sama. Mereka khawatir karena wajah sang ibu mertua juga kelihatan pucat. Rohana juga merasa sangat kesakitan di lengan kanannya, karena terlalu kuat mengayunkan pentungan kepada penjahat itu.
“Minar, kita bawa ibu sekarang ke rumah sakit.”
“Jangan, aku tidak mau.”
“Jangan bandel ya Bu, nanti Ibu akan mendapat obat, sehingga tidak merasakan sakit lagi.”
MASIH ADAKAH MAKNA 33
Indira terus melangkah mendekati rumah. Memang masih sepi. Harusnya Indira kembali, tapi ia merasa perlu untuk meyakinkannya. Ia memencet bel tamu. Tak ada jawaban. Agak lama dia melakukannya.
Di dalam, Rohana mendengarnya. Ia beranjak keluar, dan mengintip dari tirai jendela. Bayangan Indira tak tampak, tapi dia melihat mobil yang terasa asing. Itu bukan mobil ‘majikannya’.
Tersirat sebuah pikiran buruk. Bukan karena dia takut dicelakai. Kalau misalnya dia seorang jahat, lalu paling sedikit mencuri atau merampok. Bukankah dia yang orang asing dan baru sehari berada di rumah itu kemudian akan dicurigai? Tidak gampang menciptakan kepercayaan seseorang, apalagi untuk yang baru dikenalnya. Karena itulah ia membiarkan saja bel tamu terus berdering.
Indira nyaris membalikkan tubuhnya, ketika kemudian melihat bayangan di dalam rumah. Hanya bayangan karena lampu tidak menyala terang.
Indira tak pernah mendengar ada orang lain di rumah keluarga Pratama. Pikiran buruk segera menyergapnya.
Diangkatnya ponsel, dan dia hubungi Azka, dan Indira hampir tertawa mendengar penjelasannya. Ia terlalu berlebihan ternyata.
“Indi, baru tadi malam ibu membawa pembantu ke rumah. Jadi bayangan itu pastilah bayangan pembantu baru itu,” terang Azka.
“Oh, ada pembantu ya. Aku hanya takut, soalnya aku pikir rumah itu kosong. Ibu Kartika belum tampak pulang."
“Ibu sering pulang sore, tapi tak jarang pulang lebih malam. Jadi sebelum datang sebaiknya kamu menelpon ibu terlebih dulu.”
“Okey, baiklah. Aku langsung pulang saja ya, sepertinya pembantu kamu takut keluar nih.”
“Benar. Maklum, dia sudah lumayan tua, apalagi di rumah sendirian. Buruan kamu pulang, takutnya dia sudah pingsan karena ketakutan.”
Indira terkekeh, sambil kembali ke arah mobilnya, kemudian berlalu.
Rohana melongok lagi ketika mendengar mobil berlalu. Slamet … slamet … slamet, begitu batinnya, karena merasa selamat dari perkiraan yang sebelumnya membuatnya takut.
Kartika tertawa ketika si nenek menceritakan tentang kedatangan tamu yang semula membuatnya takut. Ia sudah mendengar dari Azka bahwa Indira datang untuk menemuinya, ketika dia belum pulang. Ia tidak mengira kalau si nenek takut dan tidak berani membuka pintu.
“Nenek harusnya tidak usah takut. Dia itu calon menantu saya, yang ingin menemani saya ngobrol, karena dia mengira saya sendirian di rumah.”
“Saya takutnya dia orang jahat, lalu mencuri atau merampok. Tentu saja saya takut. Kalau hal itu terjadi, pasti ibu akan mengira saya bekerja sama dengan penjahat yang melakukan pencurian atau perampokan. Ya kan? Saya baru datang, ibu tidak tahu latar belakang saya. Begitu ada saya kok kemudian ada orang jahat masuk?”
“Nenek benar, itu sebuah kehati-hatian. Tidak usah dipikirkan. Bagus kalau untuk selanjutnya Nenek melakukan itu. Hati-hati kepada sesuatu yang mencurigakan, apalagi kalau sedang sendirian. Tapi sejauh ini kampung tempat tinggal kita ini aman-aman saja kok.”
“Syukurlah kalau begitu.”
“Bagaimana kabar Nenek seharian ini?”
“Baik sekali. Saya sudah bersih-bersih rumah dan menyiram tanaman. Ibu lihat saja, nanti mana yang kurang sempurna, ibu beri tahu saya. Maklum, saya sudah tua, barangkali ada yang masih kurang dalam saya melakukan tugas saya.”
“Saya lihat semuanya bagus, bersih, rapi. Saya suka. Sekarang apakah Nenek sudah makan?”
“Tapi kok makanannya masih utuh? Nih, masih utuh lho Nek,” kata Kartika sambil membuka tudung yang kemudian dilihatnya bahwa makanannya masih utuh, atau hanya berkurang sedikit.
“Tapi saya sudah makan Bu, memang hanya sedikit. Itu cukup kok.”
“Tidak, ini sudah malam dan nenek baru makan sedikit. Tunggu sebentar, kita akan makan bersama-sama,” kata Kartika sambil masuk ke dalam kamarnya, membiarkan Rohana berdiri terpaku di samping kursi.
Ia heran, dirinya hanya pembantu, tapi ia diperlakukan seperti keluarga. Ngopi bersama, lalu makan bersama. Rasa kikuk membuatnya kemudian surut ke dapur. Memang dia baru makan sekali, dan hanya mengambil lauk sedikit. Bukan karena dirinya tidak lapar, tapi karena sungkan. Masa sih, pesanan makan untuk ‘majikan’ dan dia menyantapnya terebih dulu?
Ketika Kartika kembali ke ruang makan, ia segera duduk dan memanggil Rohana yang tiba-tiba menghilang.
“Nenek, ayo sini. Kita makan.”
Rohana mendekat dan duduk di depan Kartika dengan ragu.
“Nek, di sini Nenek berlaku baik, saya suka. Sekarang saya anggap Nenek keluarga saya juga. Jadi jangan sungkan.”
“Ibu baru saja mengenal saya. Jangan terlalu mempercayai saya. Sungguh, saya bukan orang baik.”
“Seorang yang berperilaku buruk tidak akan mau mengakui keburukannya.”
“Bukankah saya bilang bahwa saya pernah mencuri?”
“Dan Nenek mengakuinya dengan jujur, lalu bermaksud mengembalikan uang curian itu bukan? Saya melihat banyak hal baik pada diri Nenek.”
“Jangan berlebihan, Bu.”
“Sudahlah, ayo duduk dan makanlah,” kata Kartika sambil membalikkan piring yang kemudian diberikannya kepada ‘nenek’.
“Nek, kita hanya berdua. Besok pagi sudah ada lagi makanan yang dikirim. Untuk apa makanan ini kalau tidak kita habiskan? Ayo, jangan sungkan.”
Kartika benar. Itu jatah untuk mereka bertiga, untuk makan, terutama malam harinya ketika mereka sudah pulang dari bekerja.
Rohana terpaksa menuruti apa kata Kartika. Walau lapar menggerusnya, tapi dia berusaha bersikap santun. Ia mengunyah dan menelan makanannya perlahan. Rohana sudah berbeda. Rohana seperti terlahir kembali menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Ia sudah mengenal bagaimana bersujud dan berterima kasih kepada Allah Tuhannya, dan memohon ampun atas segala dosanya. Karena itulah ia merasa lebih tenang dan tak terbebani dengan apapun. Perlakuan Kartika yang lembut dan halus, membuat Rohana kemudian berkaca, bahwa perlakuan seperti itu sangat membuat orang senang, dan nyaman berbicara. Dia merasakannya.
Mengapa tidak? Rohana harus belajar banyak hal, agar menjadi manusia yang bisa membuat nyaman orang lain.
Indira datang terlambat karena tadi singgah ke rumah keluarga Azka. Ia bercerita bahwa ibu Kartika mempunyai pembantu baru, yang kelihatannya ketakutan melihat dirinya datang. Mendengar hal itu, Boy langsung meledeknya.
“Karena wajahmu itu menakutkan, jadi dia takut membukakan pintu.”
“Enak saja. Aku diluar dan agak gelap, mana kelihatan wajahku?”
”Mungkin bayangan yang kelihatan sudah seperti menakutkan, siapa tahu?”
“Memangnya aku hantu? Kalau begitu kamu juga hantu.”
”Adiknya hantu, kakaknya juga hantu, ya kan Bu?”
“Tidak ada yang hantu. Anak-anak ibu semuanya baik.”
“Tuh…” kata Indira sambil meleletkan lidahnya.
Boy hanya tertawa. Entah mengapa dia suka sekali mengganggu adiknya, dan sangat senang melihat sang adik marah-marah.
“Jadi sekarang Kartika sudah punya pembantu?” kata Monik.
“Kata Azka, baru tadi malam.”
“Pantas saja dia takut membukakan pintu, kan dia harus menjaga rumah. Kalau yang datang orang jahat, bagaimana?”
“Tuuuh,” ledek Boy lagi.
“Tentu saja bukan. Mana ada penjahat cantik seperti anak ibu ini?” kata Monik sambil merangkul Indi, membuat Indi bertambah senang karena dibela ibunya.
"Boy, tadi kakek menelpon, dan berpesan agar lamaran segera disiapkan. Bulan ini juga, kakek mau datang untuk mengantarkan kamu melamar Mia.”
“Iya, kakek sudah menelpon Boy.”
“Besok ibu akan mengajak Minar untuk mempersiapkan, apa saja yang diperlukan untuk melamar.”
“Bukankah Ibu juga pernah dilamar?”
“Ibu sudah lupa,” jawab Monik singkat. Ingatannya melayang ke arah puluhan tahun silam, di mana Tomy datang bersama kakek Drajat untuk melamar dirinya, tapi dia tidak peduli karena yang diharapkannya adalah Satria. Semuanya sudah berlalu. Monik sekarang sangat mencintai suaminya, tapi ingatan itu masih tetap melekat di hatinya.
“Ya lupa, sudah puluhan tahun yang lalu.”
“Besok Indi ikut belanjanya ya Bu.”
“Bukankah kamu harus bekerja?”
“Besok itu hari Minggu. Ya kan Bu?”
“Iya, nggak apa-apa kamu ikut. Ibu mau ngabarin ibu Minar dulu."
“Asyyiiik. Supaya aku bisa tahu, besok lamaran untuk aku itu seperti apa?”
“Yeee, ngarep. Sudah pengin dilamar ya?” ledek Boy lagi.
“Kalau iya, kenapa? Ibu juga pengin Indi segera dilamar, lalu anak-anak ibu hidup bahagia dengan keluarga barunya,” kata Monik.
“Tapi sedih dong, ibu jadi nggak ada temannya.”
“Bapak masih aktif di kantor tuh.”
“Tapi sekarangpun bapak belum pulang lhoh bu. Akhir-akhir ini bapak selalu pulang terlambat deh,” kata Indi.
“Iya. Ibu bisa mengerti. Sebenarnya bapak lebih sering keliling kota, kalau-kalau bisa ketemu nenek di suatu tempat. Ibu juga sedih memikirkannya.”
“Iya Bu. Nenek memang sangat aneh. Mengapa memilih pergi sementara hidup di rumah om Satria lebih nyaman.”
“Indi, Boy, berjanjilah kalau nanti ketemu nenek, kalian tidak menunjukkan rasa kesal, ya. Supaya nenek merasa disayang oleh semua anak cucunya. Ibu juga agak kesal melihat tingkah nenek yang mau menang sendiri tapi ibu sudah memaafkannya. Pasti ada sesuatu yang membuat nenek berbuat begitu. Itu juga yang dikatakan ibu Minar ketika berbincang sama ibu.”
“Iya Bu, kami akan bersikap baik kalau nenek sudah ketemu,” kata Boy yang diamini oleh Indi.
“Semoga nenek baik-baik saja, dan selalu merindukan kita, sehingga kalau bapak atau om Satria ketemu, mudah dibujuk untuk kembali.”
Acara lamaran untuk Mia sudah terlaksana. Sebentar lagi akan digelar sebuah perhelatan yang pasti tidak tanggung-tanggung meriahnya, karena kakek Drajat pasti juga akan mengundang semua relasi dan teman bisnisnya. Tapi Tomy tidak bisa segembira itu. Keinginan agar sang ibu ikut menikmati pesta bahagia itu terus menghimpit perasaannya.
“Alangkah bahagianya kalau ibu bisa menunggui cucunya menikah,” selalu kata-kata itu yang diucapkannya dalam setiap perbincangan.
Sebulan telah berlalu, dan Rohana sudah merasa betah tinggal di rumah keluarga Kartika. Azka sama sekali tak menyangka kalau “nenek” yang ada dirumahnya adalah nenek Rohana yang pernah dilihatnya ketika sedang membersihkan kaca mobil, bahkan ikut memaksanya pulang ke rumah keluarga Satria. Tentu saja, karena Rohana sudah berubah penampilan. Ia selalu memakai jilbab, dan tak banyak berpapasan dengan dirinya, karena nenek Rohana selalu bekerja di belakang, sedang Azka, seperti juga ayahnya, hanya ada di rumah setiap malam, di mana Kartika selalu memintanya untuk segera beristirahat. Kartika tahu, nenek sudah tua dan tidak harus bekerja terlalu berat. Itu sebabnya, dia sendiri yang melayani suami dan anaknya setiap makan. Rohana sendiri tidak begitu mengenal Azka. Dia melihat hanya sekilas, dan tak pernah perhatian karena saat ketemu cucunya, dia hanya mengomel dan marah-marah. Apalagi kemudian Indi segera mengajak Azka pergi dengan alasan mengambil mobilnya.
Yang jelas Kartika senang, karena ‘nenek Rohana’ tidak pernah berulah yang membuatnya kecewa. Pekerjaannya bagus, dan sebulan itu Rohana sudah mendapat gajinya yang pertama.
Rohana begitu senang. Ia tak harus berpanas dan berhujan ria setiap hari seperti yang dilakukannya sebelum ini. Ia bisa tidur nyaman, beribadah dengan ikhlas, dan makan kenyang, masih ditambah mendapat gaji dalam sebulan ini.
Siang hari itu pak Trimo terkejut ketika melihat Rohana datang ke warung. Ia segera memanggil Binari, maksudnya agar Binari segera mengabari Tegar bahwa ada neneknya datang. Dengan cekatan Binar meraih ponselnya.
Tapi Rohana hanya memberikan lagi sebuah amplop, yang ditolak mentah-mentah oleh pak Trimo.
“Tidak Bu, untuk apa uang ini? Ibu tolong tunggu sebentar, Binari akan mengambil amplop yang dulu Ibu berikan, masih utuh, dan akan saya kembalikan kepada Ibu.”
“Dikembalikan? Apa sampeyan tidak mendengar ketika aku mengatakan bahwa akulah yang mengambil uang sampeyan, dan aku ingin mengembalikannya?”
“Pertama, kami tidak bisa menerima uang yang tidak jelas Ibu dapatkan dari mana.”
“Itu uang aku!” kali ini Rohana berteriak dan melupakan keinginan untuk selalu bersabar dalam menghadapi apapun, karena ia merasa bahwa pak Trimo sedang menuduh dirinya melakukan hal yang tidak benar dengan pemberian uang itu.
“Begitukah? Tapi kami tetap akan mengembalikannya Bu, tolong Ibu tunggu sebentar. Binar, ambil uang itu, biar Bu Rohana menerimanya kembali,” kata pak Trimo yang melihat Binari sudah selesai menelpon.
Ketika Binari mengiyakan lalu beranjak pergi, Rohanapun melangkah pergi dengan air mata berlinang. Ia tak sudi menunggu uangnya kembali. Ia sakit hati atas ucapan yang didengarnya dari pak Trimo.
“Bu, tolong tunggu sebentar!” teriak pak Trimo yang berharap Tegar akan segera datang setelah Binar mengabarinya.
Rohana terus melangkah pergi. Tapi di sebuah pertigaan, seorang pengendara sepeda motor nyaris menabraknya. Rohana terus berlalu, dan pengendara sepeda motor itu terus menatapnya.
cerbung tien kumalasari kejora pagi
Temukan buku-buku yang berkaitan dengan cerbung tien kumalasari kejora pagi di Bakisah